Berita Sikka
Sanggar Bliran Sina: Warisan Budaya dari Watublapi untuk Dunia
Semua aktivitas dalam Sanggar Bliran Sina wajib melibatkan anak kecil dan remaja supaya mereka sadar kalau apa yang ada di
TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE-Kesibukan warga Dusun Watublapi, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka pada Selasa, 24 Juni 2025 berbeda dari hari-hari lainnya, terutama bagi para anggota Sanggar Bliran Sina. Para perempuan menggotong lembaran kain tenun dari rumah untuk dipajang di lokasi sanggar. Sejumlah lelaki dewasa sibuk menyiapkan panggung pertunjukan budaya. Hawa dingin pagi hari, awan mendung menggelayut di langit, dan semilir angin yang berdesir di antara rimbunnya pepohonan menemani aktivitas mereka.
Hari itu kampung Watublapi siap menyambut 130 wisatawan mancanegara yang turun dari kapal pesiar berbendera Prancis. Sebenarnya, ini adalah pemandangan yang biasa di Watublapi. Selama lebih dari tiga dekade, sanggar ini telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit para pelancong dari dalam dan luar negeri. Tempat ini menawarkan pengalaman yang tidak biasa; satu paket lengkap menelusuri kekayaan tradisi yang masih diwariskan sampai sekarang.
Sebelum rombongan wisatawan itu tiba, Yosep Gervasius, dan beberapa perempuan anggota sanggar menyambut terbitnya mentari dengan cara melipir ke pojokan, menggelar piong wodor. Secangkir moke, kopi panas, rokok koli, lekun, dan sirih pinang dipersembahkan untuk para leluhur. Mulutnya komat-kamit merapalkan doa dalam diam. Tradisi ini selalu dilangsungkan untuk kelancaran suatu hajatan. Setelah piong wodor dilangsungkan, barulah acara penyambutan tamu siap digelar. Anak-anak dan para perempuan penari serta para penabuh gong waning sudah bersiap dengan pakaian adat lengkap.
Baca juga: Sanggar Bliran Sina: Menyebar Pengetahuan dari Timur ke Barat
Hari itu, dari Pelabuhan Sadang Bui Maumere, para wisatawan, menggunakan 12 bus pariwisata, bertolak ke kampung Watublapi, 15 kilometer ke arah timut Kota Maumere. Disambut senyum ramah warga kampung, ratusan wisatawan itu pun menunjukkan kekaguman. Mereka diterima dengan ritus huler wair, lalu tarian hegong dan musik seruling dari kelompok sanggar Blatan Jawa mengiringi langkah kaki para wisatawan masuk ke dalam sanggar.
Di lokasi pertunjukan budaya, para wisatawan disuguhi lekun (kudapan khas masyarakat Krowe-Sikka berbahan dasar beras ketan hitam dicampur beras putih), lalu mereka juga sempat mencoba rokok koli, sirih pinang dan moke. Semua panganan itu disajikan di atas wadah yang terbuat dari tempurung kelapa dan dibungkus dengan daun pisang.
Para pemandu sigap menjawab setiap pertanyaan yang terlontar dari rasa penasaran para wisatawan. Mereka menikmatinya sambil menyaksikan atraksi tarian dan orkes kampung.
Sanggar Bliran Sina didirikan pada tahun 1988 oleh Romanus Rego untuk tujuan pelestarian dan distribusi kain tenun. Saat itu, Romanus dan istrinya Yustina Neing bersama warga Watublapi lainnya sudah sering menjual kain tenun mereka di Kota Maumere untuk membiayai hidup keluarga. Setelah Romanus Rego meninggal pada tahun 1991, pengelolaan sanggar sempat vakum selama 3 bulan, lalu pengelolaannya beralih ke pemerintah desa selama 6 bulan. Kemudian anak-anak Romanus kembali mengurus sanggar ini lagi.
Bliran Sina saat ini dikelola oleh Yosep Gervasius, salah satu anak dari Romanus Rego dan Yustina Neing. Sanggar ini telah berkembang pesat dan terkenal. Tak hanya fokus pada distribusi tenun saja, Bliran Sina kini juga menjadi spot agrowisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara.
Di Bliran Sina, para wisatawan juga bisa belajar secara langsung proses pembuatan tenun yang rumit, jenis-jenis kain tenun, mempelajari makna dari motif-motif tenun, dan jenis-jenis pakaian adat, makna dari tarian-tarian tradisional, dan sistem pengetahuan masyarakat setempat.
Metode transfer pengetahuan semacam ini rupanya membuat para wisatawan terkesan. Reice dari Belanda memuji kehangatan orang Watublapi dalam merawat nilai-nilai tradisi yang kaya akan pengetahuan.
Dia kagum dengan keramahan warga desa menyambut setiap pengunjung yang datang. Keramahan yang alami, wujud kedekatan masyarakat dengan sesama, alam dan Sang Khalik.
Cristine, seorang wisatawan dari Kanada, merasa beruntung bisa melihat langsung kekayaan tradisi yang dipertunjukkan di Sanggar Bliran Sina. Dia senang menyaksikan tarian-tarian yang indah dan mengalami kekayaan tradisi yang masih terjaga baik.
Sanggar Bliran Sina, secara performatif, berhasil mematahkan kepercayaan kolonial bahwa pengetahuan berasal dari Barat atau bersifat Eropa-sentris. Pengetahuan juga berasal dari Timur, dan kemudian menyebar ke Barat. Sejarah, pengetahuan, dan tradisi yang ada di Watublapi juga mampu menjelaskan nilai-nilai universal, terutama tentang gaya hidup selaras alam, kolektivisme dan keugaharian.
Di ujung pertemuan, sebelum kembali ke Maumere dan bertolak ke kota tujuan selanjutnya, para wisatawan yang sudah menelusuri jejak peradaban di Watublapi mulai membeli kain tenun dan suvenir khas yang tersedia di ruang galeri Bliran Sina. Transaksi jual beli dilakukan langsung dengan para penenun. Para wisawatan meninggalkan Sanggar Bliran Sina dengan kekaguman.
Sangar budaya Bliran Sina adalah ‘kebun’ kedua bagi para penenun, tempat di mana karya tangan yang sudah disemai di rumah bisa ‘dipanen’ dan dijual untuk siapa saja yang tertarik. Selain hidup dari tanaman-tanaman komoditi dari kebun di belakang rumah, para penenun juga menjadikan sanggar sebagai wadah untuk bisa menghasilkan uang dan menghidupi keluarga, yang tentu sejalan dengan misi dari mendiang Romanus Rego, pendiri Bliran Sina.
Apa yang membuat Bliran Sina berbeda? Rahasianya tentu kualitas. Ya, mereka menawarkan kualitas.
Bliran Sina sangat ketat mengkurasi kain-kain tenun yang bisa dipamerkan untuk para tamu. Syarat mutlaknya; kain harus ditenun dengan pewarna dari alam. Misalnya, warna hitam atau biru dari tumbuhan nila (tarum), warna merah dari kulit akar mengkudu, warna cokelat dari kulit pohon mahoni, warna kuning dari kunyit dan kulit kayu pohon nangka dan mangga, warna hijau dari daun nila dan daun mangga. Ini dilakukan untuk menjaga kelestarian tenun yang bersejarah dan kualitas kain dari Watublapi yang melegenda. Selain itu, penggunaan warna alami memungkinkan mereka tetap menjaga tumbuh-tumbuhan ini tetap lestari di belakang rumah mereka. Kebiasaan ini membuat para penenun tetap terkoneksi dengan alam; menjaga dan merawatnya sebagai Ibu yang memberi kehidupan.
Keindahan motif kain-kain yang dipamerkan di Sanggar Bliran Sina tak lepas dari kerja keras, komitmen dan kesetiaan para penenun dalam menjaga tradisi ini secara turun temurun. Menenun bukanlah aktivitas sekali jadi dalam waktu satu-dua hari. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan sehelai kain tenun. Prosesnya butuh ketekunan, dan tentu pengetahuan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, kemampuan menenun, yang merupakan sisa dari jejak kebudayaan Austronesia ini, diwariskan secara turun temurun sampai sekarang.
Tenun memiliki makna penting bagi masyarakat setempat, terutama perempuan. Menenun bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga merupakan identitas, penanda kedewasaan, dan sarana ekspresi kreativitas. Setiap motif tenun memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan energi, spirit, dan daya hidup yang menggerakkan masyarakat setiap hari. Kain tenun punya nilai dalam upacara kematian dan dalam ritual pernikahan—sebagai bagian dari belis atau mas kawin. Tenun juga selalu dipakai dalam ritus-ritus adat yang digelar di kampung. Oleh karena itu, terdapat cerita di balik setiap helai kain yang dihasilkan. Ada narasi di baliknya yang membuat kain tenun bernilai bagi masyarakat setempat.
1. Pupu/Huwe Kapa (Petik Kapas)
Biasanya pohon kapas ditanam di kebun atau di pekarangan rumah. Pohon ini menghasilkan buah selama satu musim saja, yaitu di musim kemarau. Jika sudah tidak berbuah lagi, pohon itu akan kering dan mati. Para penenun akan mengeluarkan kapas putih dari kelopak atau cangkangnya.
2. Wori Kapa (Jemur kapas)
Kapas putih yang masih banyak bijinya tadi dijemur di bawah sinar matahari. Jika kapas sudah kering dan ringan, maka akan dilanjutkan dengan mengeluarkan biji kapas.
3. Ngeung Kapa (Memisahkan serat kapas dari bijinya)
Untuk memisahkan biji dari kapas dipakai alat tradisional yang bernama ngeung. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan ketenangan.
4. Weting Kapa (Menghaluskan kapas)
Serat kapas yang sudah dipisahkan dari bijinya tidak serta merta sudah bersih. Masih ada kotoran yang menempel. Untuk itu, kapas dijemur dan dibentangkan lagi di atas tikar lalu dipukul-pukul dengan kayu supaya seratnya menjadi halus dan kotorannya mudah dibersihkan.
5. Ogor Kapa (Membentuk bulatan kapas supaya mudah dipintal)
Serat kapas yang sudah bersih dihaluskan lagi dengan alat seperti busur kecil, dipilin lagi menggunakan telapak tangan. Pilinan kapas ini kemudian dipintal menjadi benang panjang yang tidak terputus.
6. Jata Kapa (Pintal kapas)
Kapas yang sudah halus dan dipilih kemudian dipintal menjadi benang yang siap dipakai dalam proses menenun.
7. Wolot Ojan (Merentangkan Kapas)
Kapas yang sudah menjadi benang kemudian digulung (wolot). Prosesnya yakni dengan cara memutar-mutar benang dalam bentuk gelondong.
8. Go’an (Merentangkan benang pada pembidang pengikat)
Proses ini juga memerlukan keterampilan dan ketekunan. Benang yang siap ditenun direntangkan dengan teknik khusus.
9. Lain Kapa (Persiapan benang untuk dicelup perwarna alami).
Benang-benang yang sudah dipintal diikat sesuai dengan motif atau ragam hias geometris. Pekerjaan ini dilakukan oleh dua orang; yang satu memasukkan tiap urat benang dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, dan yang lainnya mengembalikan urat benang ke pangkalnya. Lalu mereka membentuk motif tertentu. Benang-benang yang sudah diikat dan membentuk pola-pola dengan motif tertentu tadi kemudian akan melewati proses pewarnaan benang. Proses ini juga membutuhkan waktu yang lama.
Kain tenun yang bagus justru lahir dari dapur-dapur pewarna alami di belakang rumah warga. Pewarnaan alami adalah suatu proses yang sulit dan kompleks. Perlu pengetahuan dan ketelitian supaya warna yang dihasilkan berkualitas.
Proses pewarnaan alami melibatkan penggunaan bahan-bahan alami seperti akar mengkudu untuk warna merah, daun tarum (indigo) untuk warna biru, serta kunyit atau kulit pohon lain untuk warna kuning dan coklat. Proses ini lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan pewarna kimia, namun menghasilkan warna yang lebih tahan lama dan alami.
Para penenun di Sanggar Bliran Sina menyadari keterkaitan kain tenun dengan pelestarian tumbuh-tumbuhan sekitar. Oleh karena itu, gaya hidup selaras alam yang sudah dilakoni sejak dulu harus tetap dipertahankan di tengah derasnya kehidupan modern yang semakin menggerus tradisi.
Tidak hanya perihal tenun ikat. Yang Sanggar Bliran Sina sajikan kepada pengunjung adalah pengalaman. Berkunjung ke sana seperti sebuah perayaan. Dalam balutan kain tenun, orang-orang berdendang dan menari, persis seperti perayaan pesta panen yang sakral.
Kaki penari yang menghentak tanah, tangannya yang digerakkan secara horizontal dan vertikal, dan kepalanya yang mendongak ke langit menunjukkan spiritualitas orang Watublapi yang berpusat pada Bumi yang dipijak, interaksi intim dengan sesama dan pikiran mendalam yang terarah kepada Wujud Tertinggi.
Tarian-tarian yang dipersembahkan di dalam Sanggar Bliran Sina penuh dengan simbol-simbol akan kehidupan.
Tarian Ro’a Mu’u merupakan tarian sakral yang biasanya ada dalam upacara pernikahan adat masyarakat Hewokloang. Tarian ini melambangkan restu dari kedua keluarga mempelai yang menikah. Pohon pisang ditanam di depan rumah mempelai wanita, lalu pada salah satu dahan pohon pisang itu digantungkan kain adat dengan motif simbol kesuburan perempuan.
Lalu dari pihak laki-laki akan darang membawa kuda, gading, sambil menari dengan iringan Gong Gendang. Di sinilah serah terima terjadi, kemudian penari dari pihak keluarga laki-laki akan memotong pohon pisang hias tadi.
Lalu ada beragam tarian yang dikombinasikan, yakni Tarian Awi Alu, Tarian Mage Mot dan Tarian Tua Reta Lo’u. Ketiga jenis tarian ini dipertunjukkan secara berurutan oleh belasan penari perempuan dan laki-laki. Tabuhan irama gong waning dengan berbagai jenis pukuan mengiringi jalannya tari-tarian ini.
Ketiga tarian tersebut berkaitan dengan ketangkasan perang yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki. Tarian Awi Alu menggambarkan latihan ketangkasan tubuh bagian bawah. Pada tahap ini para penari akan melompat di antara tongkat-tongkat kayu atau bambu yang dibenturkan oleh penari lain. Tongkat yang beradu akan menghasilkan bunyi. Tarian Awi Alu ini menyerupai tari tongkat yang biasa dimainkan anak-anak Pramuka.
Selanjutnya ada Tarian Mage Mot. Tujuan Tarian Mage Mot ditujukan untuk melatih ketangkasan tubuh bagian atas. Modelnya serupa dengan Tarian Awi Alu hanya saja bila pada Tarian Awi Alu tongkat ditempatkan pada jarang 20-30 cm dari tanah maka pada Tarian Mage Mot, tongkat akan ditempatkan sejajar dengan leher.
Terakhir adalah keterampilan mengintai yang disajikan dalam bentuk Tarian Tua Reta Lo’u. Pada sesi ini seorang penari pria lengkap dengan pedangnya akan dinaikkan ke sebuah tiang bambu oleh rekan-rekannya. Si penari akan bertumpu pada ujung tiang dengan perutnya. Ia berputar ke segala arah seperti sedang memantau keadaan. Tiang dipegang oleh penari pria sambil penari wanita menari di sekeliling mereka.
Pemandangan seorang pria dalam balutan busana tradisional sedang meliuk-liuk di udara dengan bertumpu pada sebatang bambu setinggi 3-4 meter, tentu saja akan mengundang decak kagum. Apalagi bila sang penari mengayunkan pedang panjang mengkilap. Sementara di bawahnya terdapat beberapa orang penari memegang erat-erat tiang bambu tersebut. Menakjubkan!
Tarian Togo biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat seperti upacara pembangunan rumah baru, pernikahan adat, atau acara syukur lainnya. Tarian Togo melambangkan ungkapan syukur dan persaudaraan masyarakat.
Sanggar Bliran Sina sadar bahwa semua yang sedang mereka lestarikan ini adalah kekayaan yang tak lekang oleh waktu. Zaman boleh berubah. Tantangan selalu ada. Akan tetapi, menjaga kekayaan tradisi adalah harga mati karena semuanya itu adalah identitas, harga diri dan kehormatan. Hilang tradisi, hilang pula identitas dan kehormatan. Oleh karena itu, tidak ada hal lain lagi yang harus dibuat. Regenerasi adalah kata kunci dari pelestarian. Anak-anak perempuan mulai belajar menenun dan menari. Mereka mengenakan pakaian adat. Anak-anak laki-laki juga belajar membuat pewarna alami dari tumbuhan, mereka juga belajar menari dan menabuh gong waning. Semua aktivitas dalam Sanggar Bliran Sina wajib melibatkan anak kecil dan remaja supaya mereka sadar kalau apa yang ada di kampung mereka adalah kekayaan yang membuat banyak orang datang dan belajar dengan rasa takjub. Sanggar Bliran Sina adalah warisan budaya dari Watublapi untuk Dunia.
Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News
Sanggar Bliran Sina Watublapi
Sanggar Budaya Bliran Sina
Sanggar Budaya Bliran Sina Watublapi
TribunFlores.com
| Peletakan Batu Pertama Jalan Yos Sudarso, Perkuat Akses Vital ke Pelabuhan Tenau Kupang |

|
|---|
| Diinterogasi Polisi Soal Kasus Penipuan, Oknum Pengacara di Flores Timur Akui Terima Uang |

|
|---|
| Sudah 6 Warga Manggarai Tewas Karena Lakalantas Tahun 2025, Polisi Minta Warga Tertib Lalu Lintas |

|
|---|
| Jurnalis Televisi di Belu Bagikan Bendera Merah Putih untuk Warga Perbatasan RI-Timor Leste |

|
|---|










![[FULL] Puncak Amarah Warga Pati Demo Desak Bupati Sudewo Lengser, Pakar: Ini Bisa Dipolitisasi](https://img.youtube.com/vi/ffnVtOw8wRU/mqdefault.jpg)

















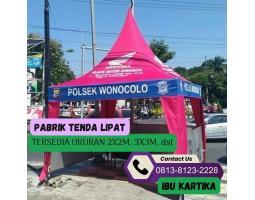
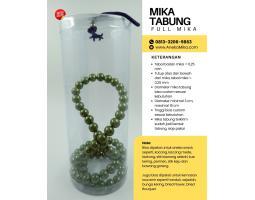







Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.